ARTICLE AD BOX
Jakarta, pendapatsaya.com --
Wacana pemberangkatan jemaah haji dan umrah melalui jalur laut kembali mencuat setelah Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkap pembahasan opsi tersebut dengan Pemerintah Arab Saudi. Meski demikian, realisasi wacana ini tetap menunggu rampungnya perbaikan akomodasi pelabuhan di Jeddah.
Rencana ini mengingatkan pada sejarah panjang perjalanan haji masyarakat Indonesia nan pada masa lampau memang dilakukan melalui laut. Sebelum transportasi udara berkembang, jemaah dari Tanah Air menempuh pelayaran panjang menuju Tanah Suci dengan kapal layar, dan kemudian kapal uap.
Dilansir DetikHikmah, perjalanan haji lewat laut memerlukan waktu hingga lima hingga enam bulan, tergantung kondisi cuaca dan musim angin.
Menurut laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Hindia Belanda sejak Liberalisasi hingga Depresi Ekonomi karya Fauzan Baihaqi, kapal layar nan mengangkut jemaah kerap tersendat angin besar dan ombak tinggi. Pemberangkatan paling sigap dilakukan pada bulan Jumadil Awal, sekitar tujuh bulan sebelum puncak haji.
Catatan perjalanan Abdullah Kadir Al-Munsyi pada 1854 menyebutkan, pelayaran dari Singapura ke Jeddah bisa menyantap waktu tiga bulan. Namun, dari pelabuhan Batavia durasinya lebih panjang lantaran banyaknya transit dan pergantian kapal.
Secara umum, kapal haji menempuh rute nan sama dengan jalur perdagangan. Banyak kapal layar saat itu juga berfaedah sebagai kapal dagang. Sepanjang abad ke-19, metode ini tetap digunakan, meskipun tak lagi memadai seiring meningkatnya jumlah jemaah.
Perubahan besar terjadi setelah dibukanya Terusan Suez pada 1869. Pada 1873, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menggunakan kapal uap untuk pemberangkatan haji.
Dalam Historiografi Haji Indonesia karya M. Shaleh Putuhena disebutkan, kapal-kapal ini wajib singgah di stasiun karantina Laut Merah, dengan masa isolasi tiga hingga lima hari tergantung status epidemiologis wilayah asal jemaah.
Data dari Conseil Superieur de Sante di Konstantinopel pada 1914 mencatat bahwa Surabaya dan Singapura tergolong wilayah nan terjangkit pes, sementara Semarang dan Batavia dicurigai menderita pandemi tersebut. Kapasitas stasiun karantina sering kali tak mencukupi, apalagi jemaah sempat dialihkan ke Toor, Mesir.
Saat Perang Dunia I, stasiun karantina tidak beroperasi, sehingga jemaah asal Indonesia tidakhadir menunaikan haji. Baru setelah 1923, karantina kembali dilakukan di Jeddah di bawah otoritas Inggris.
Setelah proses karantina, jemaah melanjutkan perjalanan menuju Yalamlam untuk mengambil miqat. Banyak pula nan mengenakan ihram di Jeddah. Kapal-kapal umumnya tiba di Jeddah pada akhir Zulkaidah.
Perkembangan prasarana pada awal abad ke-20 memungkinkan jemaah dari Jawa bagian barat berangkat melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Data menunjukkan peningkatan signifikan, dari 5.987 jemaah pada 1912 menjadi 8.632 jemaah pada 1913.
Perjalanan dengan kapal uap dari Batavia ke Jeddah memerlukan waktu antara 19 hingga 49 hari, jauh lebih sigap dibanding kapal layar. Namun demikian, total proses keberangkatan dan kepulangan tetap menyantap waktu sekitar enam bulan.
Beberapa kloter terakhir apalagi berangkat saat Ramadan alias Syaban, dan tiba di Jeddah mendekati bulan Syawal. Tak jarang jemaah haji merayakan Idul Fitri dan Idul Adha di Makkah.
Sayangnya, kondisi kapal tidak selalu ideal. Dalam arsip laporan haji 1912 nan tercatat di Arsip Nasional Republik Indonesia, dari 18.535 jemaah, sebanyak 2.634 meninggal dunia. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya menjadi 3.158 dari total 26.321 jemaah.
Sebelum diatur pemerintah kolonial, jemaah Indonesia sering menumpang kapal jual beli VOC alias Inggris hingga India alias Teluk Aden. Pada 1912-1913, pemerintah kolonial mewajibkan penggunaan kapal milik Kongsi Tiga dari pelabuhan-pelabuhan Hindia Belanda, seperti Tanjung Priok, Padang, dan Singapura.
Setelah itu, Pemerintah Hindia Belanda membuka kesempatan bagi perusahaan lain untuk mengangkut jemaah. Jumlah jemaah pun meningkat drastis. Pada 1921, tercatat 23.665 jemaah berangkat dari Tanjung Priok, 5.310 dari Padang, dan sisanya dari pelabuhan lain.
Dilansir laman Kementerian Agama, pada musim haji 1950 setelah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia memberangkatkan 9.907 jemaah menggunakan kapal laut dengan kapabilitas 10.000 penumpang.
Tahun berikutnya, Menag saat itu Wahid Hasjim kembali menggulirkan wacana lama: Indonesia mempunyai kapal haji sendiri. Usaha pengumpulan saham dari calon jemaah sempat dilakukan, namun kandas dan biaya dikembalikan.
Cita-cita itu baru terwujud pada 1960-an, saat PT. Pelayaran Arafat berdiri. Perusahaan ini merupakan hasil kerjasama umat Islam dan pemerintah nan diinisiasikan Presiden Soekarno, dengan tokoh-tokoh nasional seperti Letjen H.M. Muljadi Djojomartono, Jenderal A.H. Nasution, Ali Sadikin, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai pendirinya.
Pada 1965, PT. Pelayaran Arafat membeli tiga kapal laut untuk mengangkut jemaah. Saat itu, usulan untuk menyelenggarakan haji lewat udara ditolak pemerintah.
Sayangnya, perusahaan mengalami kesulitan manajemen dan finansial di tengah lonjakan jumlah jemaah. Sekitar tahun 1976, PT. Pelayaran Arafat dinyatakan pailit. Pemerintah kemudian memutuskan untuk menghentikan pengangkutan jemaah haji melalui laut pada 1979.
Sejak saat itu, seluruh jemaah haji Indonesia diberangkatkan menggunakan pesawat udara.
Baca buletin lengkapnya di sini.
(kay/dal)
[Gambas:Video CNN]

 4 jam yang lalu
4 jam yang lalu
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3993067/original/008641900_1649750190-20220412-FOTO---LONGSOR-Herman-7.jpg)


:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5280954/original/009632900_1752299185-c1c8ad8b-1c19-4eff-8aa1-bdcf76216eea.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5280952/original/004587900_1752298968-IMG_20250712_044055.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5095947/original/048610200_1736956285-Screenshot_2025-01-15_223758.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3982312/original/095510200_1648824327-20220401-Masjid_Agung_Al-Azhar_Jakarta_Gelar_Sholat_Tarawih-2.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5128214/original/016297600_1739232349-Screenshot_2025-02-11_070303.jpg)
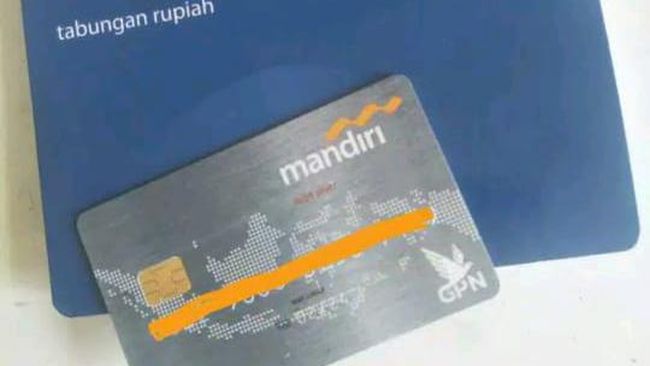



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5039131/original/070727500_1733499177-IMG_6965.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4014380/original/069997700_1651744733-20220505-Arus_Balik_Kereta_Api_Jarak_Jauh_di_Stasiun_Pasar_Senen-6.jpg)
 English (US) ·
English (US) ·  Indonesian (ID) ·
Indonesian (ID) ·